Mengenal kopi bisa lewat apa saja, secangkir kopi, aroma seduhan, tulisan, atau bahkan cerita dari penikmatnya yang tak sengaja sayup-sayup terdengar. Dewi Lestari sudah membuktikannya dengan bukunya yang fenomenal Filosofi Kopi yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama. Bahkan tahun lalu sempat ramai istilah “Kopi dan penikmat senja”.Pembuka lagu Senja Senja Tai Anjing mungkin juga terinspirasi dari perpaduan kedua istilah yang teramat syahdu itu.
Kopi paling nikmat bagi sebagian orang akan menyisakan rasa pahit yang sangat membekas di lidah. Beberapa orang penyuka kopi tubruk untuk menikmati rasa pahit paling sempurna harus menunggu ampasnya mengendap. Baru menikmati pahitnya serupu-demi seruput hingga tersisa lethek-nya saja. Orang-orang modern yang digerakkan oleh kehidupan yang bergerak teramat cepat dipaksa menikmati kopi instan atau kopi seduhan yang dicampur minuman lainnya. Bagaimanapun cara pengolahannya sensasi pahit yang khas dalam kopi takkan pudar. Kopi selalu punya ruang untuk hadir dalam kehidupan penikmatnya.
Kali ini saya ingin menceritakan dua kejadian yang sama sekali tak berhubungan dengan kopi tapi tak bisa lepas dari kopi. Sore ini dalam perjalanan menuju Lahar Pang saya melihat beberapa hal yang jarang sekali saya jumpai. Ketika melintasi sebuah gereja tua bernama Bethel di bawah hujan deras, saya melihat pemuda-pemuda bertubuh atletis berlari-lari di jalanan. Kejadian itu mengingatkan pada sepenggal pengalaman di masa kecil saat berlari dibawah hujan yang mengguyur. Membangunkan pengalaman di masa lampau yang sudah terkubur berbagai pengalaman lainnyasangat berarti buat saya. Ternyata di masa lalu saya pernah mengalami kehidupan yang tak perlu dibandingkan dengan pahitnya kopi.
Cerita kedua adalah tentang tekad Guru Ngaji saya dan keistiqomahannya dalam kebaikan. Bahkan menurut saya ia melakukan hal baik dengan sangat mulia. Setiap minggu sore Guru Ngaji saya menempuh jarak sekitar 40 km dari rumahnya untuk mengajar ngaji di sana dan pulang dari sana terkadang hampir tengah malam melewati jalanan di antara pepohonan hutan yang menjulang. Sore itu sebenarnya saya mengekor Guru Ngaji saya yang akan mengajar ngaji di sana Ba’da Magrib. Saat melintas desa sebelum lereng gunung Kelud, kami menjumpai bapak-bapak yang berdiri di tengah jalan untuk meminta sumbangan pembangunan masjid. Apa yang dilakukan Guru Ngaji saya? Ia yang mengendarai motor saya menyalakan sein dan berhenti sejenak untuk memberikan uang kepada bapak-bapak tadi. Sore itu bukan kali pertama Guru Ngaji saya melakukan hal itu, minggu lalu juga, dan beberapa minggu lalu saat di Lumajang ia juga berhenti untuk memberikan uang kepadaPak Ogah yang sedang kepanasan mengatur lalu lintas. Bukan hanya rasa dari kopi terbaik saja yang konsisten, manusia-manusia terbaik pun juga begitu.
Sesampainya di Lahar Pang, saya langsung memesan semangkuk mie instan dan segelas jus alpukat. Sembari mengisi perut, saya mengobrol dengan Sahabat Guru Ngaji saya tentang kondisi di sana pasca letusan gunung Kelud tahun 2014. Lahar Pang adalah desa di lereng Kelud bagian barat laut dan letaknya paling dekat dengan puncak gunung Kelud. Ketika Kelud Meletus Lahar Pang menerima beratus-ratus ton tumpukan pasir dan batu yang dimuntahkan dari kawah di puncak gunung Kelud. Karena letusan tersebut Lahar Pang sepertinya tak punya harapan lagi. Tapi saya masih penasaran bagaimana orang-orang di Lahar Pang membuka harapan-harapan baru pasca kejadian itu.
Saya jadi teringat sebuah ungkapan yang ditulis di atas tampah yang ditempelkan di dinding Lamor Coffe, “Mungkin Tuhan menciptakan kopi agar kita semua bisa berteman”. Kata semua yang terselip pada tulisan itu mungkin menggambarkan kehidupan sehari-hari penduduk Lahar Pang yang amat dekat dengan Kelud. Bagi saya kenikmatan secangkir kopi Lahar Pang sudah sepaket dengan berbagai cerita yang hadir disana dan cerita lain masih akan diseduh. Dan, cerita ini belum selesai ditulis.

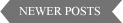


0 komentar:
Posting Komentar